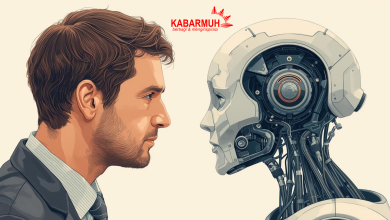Oleh: Ahmad Hermanto, Mahasiswa Pendidikan Agama Islam FAI UM Metro dan Ketua Bidang Pengembangan Prestasi Keolahragaan PD IPM Lampung Timur
Di zaman serba digital seperti sekarang, ketika segalanya diukur lewat angka like, views, followers, eksistensi manusia perlahan-lahan tak lagi dibentuk oleh nilai, kejujuran, atau kontribusi nyata, tapi oleh seberapa sering ia muncul di layar orang lain. Kita, sadar atau tidak, mulai lebih sibuk membangun citra daripada memperdalam makna. Kita lebih peduli dengan bagaimana orang melihat kita, dibanding siapa sebenarnya diri kita. Media sosial menjelma jadi semacam etalase hidup, tempat kita menampilkan versi paling menarik dari diri sendiri: yang estetik, yang tersenyum bahagia, yang berprestasi, yang sukses. Padahal, sering kali semua itu hanya permukaan. Di baliknya, tersembunyi kegelisahan, kekosongan, kelelahan, bahkan krisis identitas yang tak pernah muncul di feed.
Kita jadi terbiasa mengedit realita agar tampak ideal. Menghias kekurangan dengan filter. Menyembunyikan kegagalan di balik caption bijak. Kita menjadi sangat piawai membentuk kesan, tapi sering kali kehilangan keaslian. Ketika kita terlalu fokus pada “tampilan”, kita mulai lupa pada “substansi”. Ketika kita hanya mengejar yang viral, kita mengabaikan yang bernilai. Ketika kita hanya ingin cepat terlihat, kita rela memangkas proses yang seharusnya kita jalani.
Kita jadi takut terlihat biasa. Takut tidak dikenal. Takut tenggelam dalam keramaian. Ketakutan itu mendorong kita untuk terus muncul, terus eksis, terus tampil. Bahkan jika itu berarti menjadi orang lain. Bahkan jika itu berarti menggadaikan prinsip, integritas, dan jati diri. Kita mulai mengejar eksistensi dengan cara-cara instan seperti sensasi, drama, kontroversi. Kita rela menciptakan persona palsu demi validasi dari orang-orang yang bahkan tak benar-benar mengenal kita.
Padahal, pertanyaannya sederhana: siapa kita ketika tak ada yang menonton? Ketika semua layar mati, ketika tidak ada yang menyorot, ketika tidak ada yang memuji atau memberi komentar? Apakah kita masih bisa merasa cukup? Masih bisa merasa berharga? Itulah esensi sejati dari keberadaan kita. Sebab yang benar-benar membentuk manusia bukanlah sorotan, bukan popularitas, tapi proses yang dilalui dalam diam, dalam senyap, dalam perjuangan panjang yang tak selalu disukai algoritma.
Sayangnya, dalam budaya hari ini, yang pelan dianggap tertinggal. Yang mendalam dianggap membosankan. Yang tulus dianggap kurang menarik. Kita seperti hidup dalam kompetisi terus-menerus untuk menjadi pusat perhatian. Padahal, perhatian itu mudah datang dan mudah pula hilang. Hari ini kita bisa viral, besok kita bisa dilupakan. Jika kita hanya hidup demi sorotan, maka hidup kita akan cepat habis ditelan ekspektasi dan tekanan yang tak pernah selesai.
Tapi, apakah kita harus terus begitu? Terus mengikuti arus? Terus membentuk diri demi disukai, daripada memahami diri agar bisa hidup bermakna? Saya percaya, masih banyak anak muda yang tidak terjebak dalam kegilaan ini. Mereka yang tidak sibuk mengejar eksistensi palsu, tapi fokus membangun esensi sejati. Mereka yang diam-diam membaca, belajar, mencipta, mengabdi. Mereka yang lebih memilih kualitas daripada popularitas. Mereka yang membangun sesuatu yang bernilai walau tidak banyak diketahui orang.
Justru mereka inilah yang bangsa butuhkan. Bukan mereka yang paling sering ada, tapi mereka yang paling punya pengaruh nyata. Bukan yang paling viral, tapi yang paling konsisten. Bukan yang paling mencolok, tapi yang paling berdampak. Karena eksistensi sejati hanya bisa tumbuh dari esensi yang kuat. Tanpa esensi, eksistensi hanyalah panggung kosong. Cepat dikenal, tapi juga cepat terlupakan.
Menjadi seseorang yang benar-benar hidup bukan berarti harus selalu terlihat. Terkadang, justru di balik layar itulah proses paling penting sedang terjadi. Saat kita berjuang dalam kesunyian, bertumbuh tanpa disorot, bekerja tanpa banyak pujian, itulah momen yang membentuk karakter kita. Menjadi kuat tanpa pamer. Menjadi bijak tanpa disanjung. Menjadi terkenal tanpa validasi digital.
Hari ini, kita dihadapkan pada pilihan: ingin dikenal banyak orang tapi kehilangan diri sendiri, atau ingin mengenal diri sendiri meski tak banyak dikenal orang? Ingin terus hidup dalam pencitraan, atau ingin hidup dalam ketulusan? Ingin memburu perhatian cepat, atau membangun dampak jangka panjang? Hidup yang bermakna tak diukur dari banyaknya sorakan, tapi dari nilai-nilai yang kita pegang, dari kebaikan yang kita tebarkan, dari dampak nyata yang kita lakukan.
Maka, mari kita bertanya lagi pada diri sendiri, untuk apa kita hidup: untuk terlihat, atau untuk benar-benar menjadi? Untuk dikenang karena popularitas, atau dihormati karena integritas? Untuk tampil, atau untuk tumbuh? Dunia hari ini mungkin sedang ramai dengan keterlihatan, tapi justru karena itulah kita butuh lebih banyak orang yang memilih kedalaman. Yang memilih untuk tidak hanya tampil mengesankan, tapi hidup dengan makna. Yang memilih membangun pondasi kuat meski tak tampak, karena mereka tahu, saat badai datang, yang akan bertahan bukanlah yang paling viral, tapi yang paling berakar.
Jadi, jika hari ini kamu merasa tertinggal karena tak banyak dilihat orang, ingatlah bahwa yang hebat tak selalu terlihat. Dan yang terlihat, belum tentu hebat.